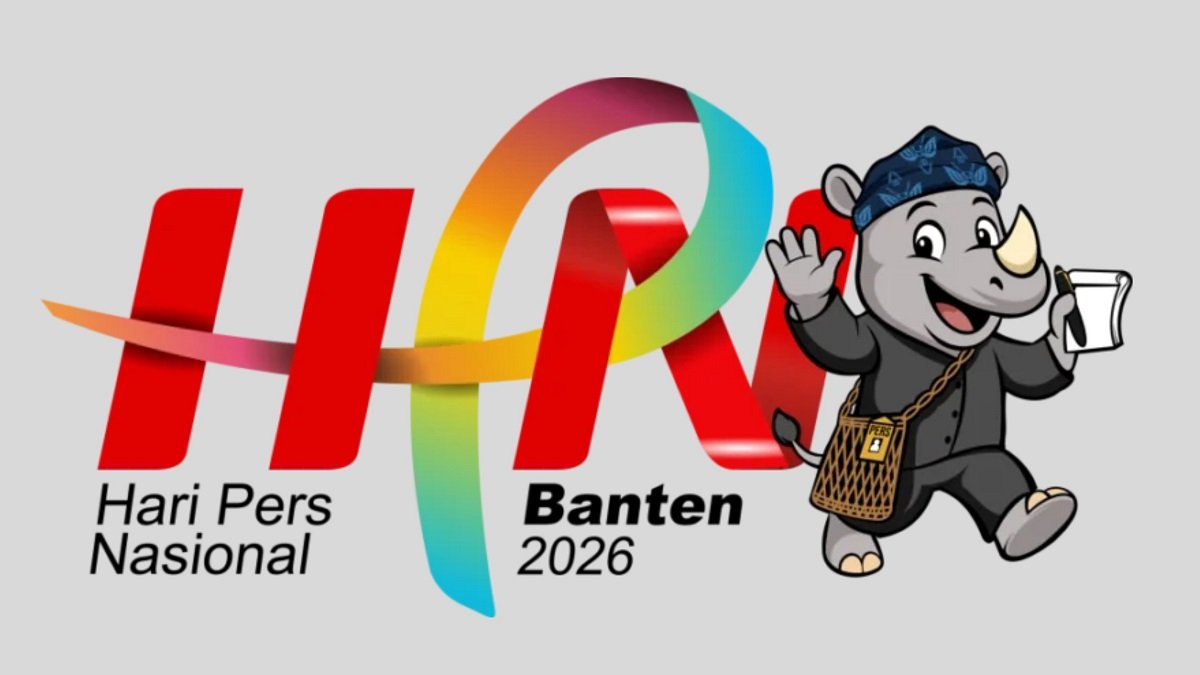EDITORIAL, BOMBANAPOST.COM — Hari Pers Nasional kerap dipenuhi seremoni dan pujian terhadap kemerdekaan pers. Namun perayaan semacam itu sering menutup kenyataan yang lebih mendesak: pers Indonesia hari ini tidak sedang kekurangan kebebasan, melainkan sedang diuji keteguhannya menjaga nurani di tengah tekanan industri.
Tidak ada yang keliru dengan menyebut pers sebagai industri. Di era digital, media tidak hidup dari idealisme semata. Gaji wartawan, biaya liputan, teknologi, dan distribusi menuntut keberlanjutan ekonomi. Media yang menutup mata terhadap logika bisnis justru rawan tumbang atau, lebih berbahaya lagi, bergantung pada kekuasaan dan kepentingan tersembunyi. Dalam konteks ini, industri adalah syarat hidup pers.
Masalah muncul ketika logika industri tidak lagi ditempatkan sebagai alat, melainkan menjadi tujuan. Ketika klik menjadi mata uang utama, verifikasi sering kali dianggap beban. Ketika trafik menjadi ukuran segalanya, kebenaran dipaksa bersaing dengan sensasi. Di titik inilah pers mulai kehilangan watak dasarnya dan perlahan berubah menjadi sekadar pabrik konten—ramai, cepat, tetapi hampa.
Pers tidak dilahirkan untuk menyenangkan algoritma, apalagi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan dan modal. Ia hadir sebagai institusi sosial yang menjaga ruang publik tetap rasional. Ketika fungsi ini dikorbankan atas nama bisnis, yang runtuh bukan hanya etika jurnalistik, tetapi juga kepercayaan publik. Dan pers yang kehilangan kepercayaan, sejatinya telah kehilangan legitimasi moralnya.
Sering dikatakan bahwa pers menghadapi dilema antara idealisme dan industri. Pandangan ini menyesatkan. Pers tidak dituntut memilih salah satu, melainkan dituntut mengendalikan keduanya. Industri adalah mesin yang membuat pers bergerak, sementara idealisme adalah kompas yang menentukan arah. Mesin tanpa kompas akan melaju liar dan merusak. Kompas tanpa mesin hanya akan berputar di tempat. Pers yang sehat adalah pers yang sanggup menahan laju mesinnya ketika arah mulai menyimpang.
Di tingkat media lokal, ujian ini terasa lebih keras dan lebih nyata. Keterbatasan sumber daya, kedekatan dengan elite, serta tekanan untuk bertahan hidup membuat godaan kompromi datang setiap hari. Namun justru di ruang inilah integritas pers diuji secara sesungguhnya. Bukan lewat jargon independensi, melainkan lewat keputusan redaksional yang konsisten—apa yang diberitakan, apa yang ditolak, dan sejauh mana keberpihakan pada publik dijaga.
Hari Pers Nasional semestinya menjadi momen evaluasi, bukan sekadar perayaan. Pers perlu bertanya pada dirinya sendiri: apakah ia masih berdiri sebagai penjaga akal sehat publik, atau telah larut menjadi bagian dari kebisingan yang ia ciptakan sendiri. Kebebasan pers kehilangan maknanya jika tidak disertai tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, pers yang layak dipertahankan bukan yang paling keras suaranya atau paling tinggi trafiknya, melainkan yang mampu bertahan sebagai industri tanpa menjual nurani. Di situlah martabat pers diuji dan di situlah masa depannya ditentukan. (redaksi)